Jika kau pikir pakaian eksoskeleton Elysium sangat keren dan Pacific Rim sangat komikal (meskipun herois), atau jika kau pikir Starship Trooper sangat gila dan The Matrix: Revolution sangat keji, mungkin kau sudah bisa meramalkan isi Edge of Tomorrow. Awalnya, film ini memang punya rasa thriller sci-fi yang familiar—terutama soal invasi aliennya. Namun, ternyata Edge of Tomorrow lebih cerdas dan rapi dari kelihatannya.
Saat film dimulai dengan informasi tentang malapetaka yang menimpa bumi, kita tahu bahwa alien yang bernama ‘Mimic’ telah menginvasi bumi. Mayor William Cage (Tom Cruise) segera terjebak dalam sebuah kondisi yang tak diinginkannya—yaitu maju dalam pertempuran. Tanpa persiapan dan terpaksa, Cage maju dalam pertempuran; dan ternyata ia baru tahu bahwa ia dapat hidup berkali-kali setiap kali ia mati. Bingung dan tanpa arahan siapapun, ia akhirnya bertemu orang yang dapat memahami kondisinya—Rita Vrataski (Emily Blunt), sang “Malaikat Verdun.” Masalahnya, semua justru makin rumit meskipun Cage bisa hidup ratusan kali lagi.
Di Permukaan, EoT serasa dilapisi dengan tempelan plot-plot yang tidak orisinil. Namun jika dilihat dengan seksama, kita akan tahu bahwa EoT lebih dari itu. Pengaruh Groundhog Day memang nampak, begitu juga pengaruh The Matrix, namun, EoT mampu memanfaatkan plot berputar-putarnya dalam membuat hiburan yang segar dan orisinil. Yang paling keren, setiap kali jagoan kita mati dan hidup lagi, kita takkan melihat kejadian yang sama lagi—semuanya dibuat berbeda berdasarkan tingkat pemahaman si jagoan akan keadaannya. Sutradara Doug Liman nampaknya tahu betul bahwa pola “hidup-mati-ulangi lagi” ini punya titik jemu yang dapat membuat penonton frustasi sekaligus bosan; oleh karenanya, ia memutar arah cerita di beberapa titik krusial. Resikonya memang membuat penonton makin gemas dan geregetan, namun cara ini mampu menghindarkan film ini dari kesan monoton. Pada akhirnya, plot rapi ini mampu membuat repetisi ini tidak melelahkan dan tidak mudah diprediksi; justru rasanya seperti bermain game arcade dengan ‘restart’ tanpa batas.
Singkat kata, Liman telah mengadaptasi All You Need is Kill karya Hiroshi Sakurazaka menjadi lebih implisit. Di tengah film, kita akan sadar bahwa bukan hanya “membunuh” saja yang kita perlukan, tapi “pemecahan masalah” yang lebih penting. Ketika kita masuk lebih dalam kegentingan para karakter, kita segera tahu bahwa akting Cruise dan Blunt yang terkesan setengah matang ini semata-mata karena pengaruh karakter yang mereka perankan. Keduanya bukan pahlawan siap saji—mereka hanya korban dari situasi (dan kemampuan) mereka sendiri. Jika karakter Blunt terlihat lebih siap dan waspada, itu karena karakternya sudah lebih dulu menghadapi situasi ini. Selain itu, pace yang kilat juga tak memungkinkan kita melihat perkembangan karakter; karena itulah, ekstra kredit untuk karakter nampaknya urung diberikan.
Pada akhir film setelah semua kegilaan yang dialami, saya memang merasa agak kecewa. Akhir film ini terkesan main aman saja, padahal jika film ini berakhir dengan lebih berani pasti semuanya akan lebih menegangkan. Namun EoT telah membuktikan bahwa film ini sudah lebih dari sekedar hiburan musim panas saja. Film ini punya keberanian untuk memutarbalikkan familiaritas sci-fi musim panas dengan ‘time loop’ yang berani dan plot yang rapi. EoT pantas menjadi sleeper-hit tahun ini.
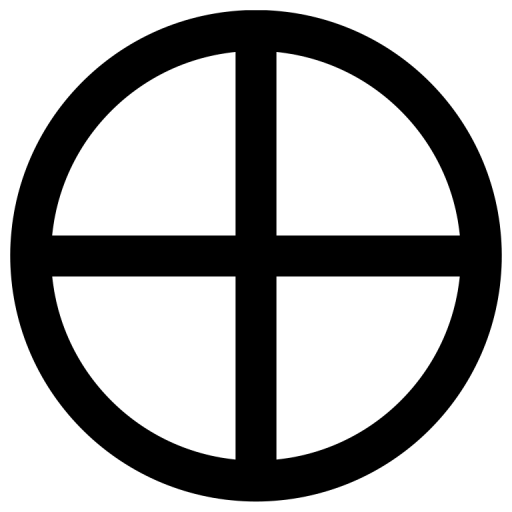
Leave a Reply