READ THIS REVIEW IN:
Saat Sersan Satu Don ‘Wardaddy’ Collier—Brad Pitt yang kembali memburu Nazi—berkata “wars are never going anywhere” dengan lantang; dia berkata jujur, perang takkan ke mana-mana. Karakternya telah mendeskripsikan seluruh jalan cerita Fury. Mendekati akhir Perang Dunia II, pasukan Sekutu berhasil menembus pertahanan Jerman—akhir perang mendekat, namun, mereka tahu bahwa musuh mereka takkan sudi menyerah di tanah sendiri.
Di tengah-tengah perang, Don mengkomandoi sebuah kompi dengan tank Sherman berisi 4 kru lain—Boyd alias Bible (Shia LaBeouf), Trini alias Gordo (Michael Peña), Grady alias Coon-Ass (Jon Bernthal) dan anak baru, Norman alias Machine (Logan Lerman). Mereka bertempur dari satu kota ke kota lain menghancurkan pasukan Jerman yang tersisa. Kalah jumlah dan kalah canggih, pleton dalam tank bernama Fury ini bertahan mati-matian di tanah musuh. Namun, perang memang takkan ke mana-mana.
Selama dua seperempat jam, Fury menampilkan horror yang nyata tentang PD II—yang memang membuat kita yakin bahwa perang benar-benar neraka yang nyata. Sebagai film perang, Fury sangat keras, kejam, dan intense; namun, poin utama film ini justru adalah terror claustrophobic yang selalu menghantui quintet protagonis. Pertempuran dengan tank punya koreografi yang sangat dinamis—menjadikannya santapan utama di film ini. Sutradara David Ayer (penulis Training Day dan Fast & Furious pertama) telah membuktikan bahwa tank boleh jadi senjata perang paling mematikan, sekaligus, tempat perlindungan terpayah’ bagi siapapun yang mengendarainya.
Yang membuat kengerian makin nyata justru adalah chemistry antar A-lister-nya. Quintet kru Fury bukanlah pahlawan Amerika atau mesin pembunuh tipikal film perang; mereka hanyalah pria-pria yang depresi—muak dengan perang, muak dengan kematian—tapi mereka harus bertahan karena mereka yakin inilah “best job they’ve ever had.” Transformasi luar biasa menaungi karakter LaBeouf dan Lerman; selain itu, lelucon Peña & Bernthal kadang-kadang lucu, namun jujur saja, ada kepahitan yang terasa. Dalam chemistry yang sebegitu luar biasa, tentu ada satu fakta yang segera terlupakan—perselisihan antara Pitt dan LaBeouf saat produksi film ini (Google saja berita ini ;))
Saya memang tidak terlalu suka film perang—tapi saat Fury berakhir dan ketegangannya masih terasa sampai credit rolls—saya yakin bahwa Fury adalah film perang terbaik yang saya tonton beberapa tahun belakangan. Hampir semua momennya terasa menegangkan; bahkan di momen yang lebih “rileks”, atmosfernya masih terasa mencekam dan membuat perasaan “insecure.” Di tambah dengan finale yang gila-gilaan, Fury benar-benar memberi perasaan tidak nyaman sampai selesai menonton di bioskop.
Tak dipungkiri, Fury banyak dibalut klise dan kekerasan yang terlalu dahsyat; ditambah, Fury tidak punya resolusi yang “membedakannya” dari film perang lain. Meskipun begitu, Fury berhasil menggabungkan kekerasan, intensity serta berbagai macam ledakan dengan drama yang dibumbui akting luar biasa dari A-lister-nya sekaligus pertempuran tank dengan koreografi yang mencengangkan.
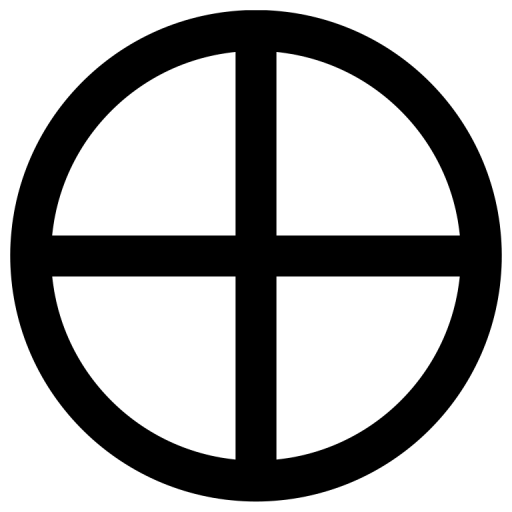
Leave a Reply